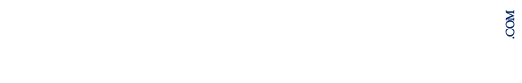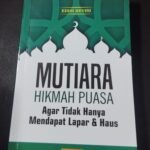Now Reading: Krisis Ekonomi dan Perbankan 1998 serta Kebijakan Penanganannya
-
01
Krisis Ekonomi dan Perbankan 1998 serta Kebijakan Penanganannya
Krisis Ekonomi dan Perbankan 1998 serta Kebijakan Penanganannya

Krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di Indonesia pada 1997/1998 berlangsung sangat cepat dan dahsyat sehingga akibatnya bersifat multidimensi. Tidak terbayangkan sebelumnya, setidaknya sampai Juni 1997, krisis yang sangat hebat menghempaskan hampir seluruh pencapaian sektor ekonomi yang telah bertumbuh sangat pesat.
Indonesia bukan satu-satunya Negara di Asia yang diterjang krisis keuangan, namun termasuk yang sangat parah. Pada Juni 1997, Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, laju inflasi di Indonesia rendah, surplus perdagangan lebih dari US$900 juta, sedangkan jumlah cadangan devisanya cukup besar, lebih dari US$20 miliar. Namun saat itu nilai pinjaman valuta asing perusahaan-perusahaan swasta cukup besar, banyak diantaranya yang tidak hedging.
Pemerintah dan Bank Indonesia masih sangat percaya bahwa kondisi ekonomi dan moneter “baik-baik saja” ketika terjadi penurunan niai tukar Baht Thailand pada Juli 1997. Nilai tukar rupiah yang semula dipatok Rp 2.380 per US$1 terguncang dan menimbulkan kepanikan masyarakat sehingga kursnya makin merosot. Kurs US$ makin menguat terhadap rupiah, tercatat menyentuh Rp 11.000 pada awal 1998 bahkan sempat mencapai Rp 17.000 beberapa waktu kemudian.
Banyak factor yang mempercepat laju krisis moneter dan keuangan di Indonesia, namun menurunnya kepercayaan (trust) kepada pemerintah merupakan kunci yang menyebabkan keadaan berkembang memburuk. Pemerintah kelihatan kurang percaya diri, misalnya, terlalu mengikuti pendapat dan saran World Bank dan International Monetary Fund (IMF) dalam pengendalian kurs rupiah dan penutupan sejumlah bank.
Kebutuhan US$ yang meningkat pada akhir tahun untuk pembayaran bunga dan cicilan utang makin menyebabkan tekanan terhadap niai tukar rupiah. Akibatnya, kurs rupiah makin ambruk. Kepercayaan rakyat juga makin menurun ketika pemerintah menyodorkan angka-angka RAPBN 1998/1999 yang diumumkan 6 Januari 1998, yang dinilai tidak realistis. Krisis yang menandakan kerapuhan fundamental ekonomi tersebut dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya rupiah secara dramatis menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar. Peringkat internasional bank-bank besar tersebut memburuk, tak terkecuali surat utang pemerintah, peringkatnya ikut lengser ke level di bawah “junk” atau menjadi sampah.
Pada kurun waktu itu, ribuan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan terpukul cukup parah. Risiko lanjutannya adalah terjadinya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.
Akibat PHK dan melesatnya harga-harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Ketika itu, angkanya tercatat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Pendapatan per kapita yang mencapai US$1.155 /kapita pada 1996 menciut menjadi US$610 /kapita pada 1998. Dua dari tiga penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), berada dalam kondisi yang sangat miskin pada 1999.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 berubah menjadi nol (0) persen kuartal terakhir. Angkanya terus menciut tajam menjadi kontraksi (-) sebesar 7,9 persen pada kuartal I/1998, kontraksi (-) 16,5 persen kuartal II/1998, dan terus terkontraksi (-) 17,9 persen kuartal III/1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah mencapai 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.
Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya alias tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah. Dunia bisnis sudah tercekik akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global. Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode sama 1997, sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36 persen.
Krisis ekonomi, keuangan dan perbankan yang terjadi dalam waktu singkat, telah menimbulkan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Keadaan yang terus memburuk menimbulkan kepanikan dimana-mana, apalagi kemudian terjadi kelangkaan pasokan barang kebutuhan masyarakat. Terlihat antrian nasabah bank yang akan menarik dana mereka, demikian pula antrian di pusat-pusat perbelanjaan. Gelombang demonstrasi terus terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain yang meminta pertanggungjawaban pemerintah, bahkan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto.
Ujung dari krisis multi dimensi di Indonesia, yang berlangsung selama beberapa bulan, adalah pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Wakil Presiden BJ Habibie kemudian diambil sumpahnya menjadi Presiden RI, yang sekaligus menandai dimulainya era reformasi.
Kisis Perbankan
Salah satu keputusan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menyikapi perkembangan ekonomi dan moneter yang memburuk adalah pemberian bantuan likuiditas kepada perbankan yang mengalami kesulitan. Sebagai lender of the last resort, BI menyetujui permintaan pemerintah untuk mengucurkan suntikan dana yang disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Keputusan pengucuran BLBI disetujui dalam Sidang Kabinet Terbatas Ekkuwasbang-Prodis pada 3 September 1997 yang dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto. Bantuan disesuaikan dengan permasalahan bank. Misalnya, fasilitas diskonto untuk mengatasi gangguan akibat kesenjangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana bank. Lalu, pembelian SBPU atau surat utang bank oleh BI. Saat itu banyak bank yang tidak sehat. Satu bulan setelah BLBI digelontorkan, jumlah bank bermasalah mencapai 39 bank.
BI meminta perbankan untuk menggunakan dana BLBI hanya untuk memenuhi kebutuhan pihak ketiga (masyarakat). Ditengarai banyak terjadi penyimpangan, namun karena keadaan berkembang makin buruk, maka BI terus menggelontorkan bantuan likuiditas. Sebab, bank dalam krisis berat.
Presiden juga menugaskan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- Agar diupayakan penggabungan atau akuisisi terhadap bank-bank yang secara nyata tidak sehat oleh bank yang sehat.
- Jika upaya ini tidak berhasil, bank-bank tersebut supaya dilikuidasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin penabung, terutama pemilik simpanan kecil.
Sebagai langkah awal penyehatan perbankan yang dirumuskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan dukungan IMF disepakati bahwa tindakan melikuidasi bank yang tidak solvent merupakan sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka restrukturisasi perbankan. Ketika itu BI mencatat ada tujuh bank swasta nasional yang layak dicabut izinnya, namun IMF menyarankan lebih dari angka itu. Setelah melalui serangkaian kajian akhirnya disepakati keputusan untuk melikuidasi 16 bank. Yaitu:
- Bank Harapan Sentosa
- Sejahtera Bank Umum
- Bank Pacific
- South East Asian Bank
- Bank Pinaesaan
- Bank Anrico
- Bank Umum Majapahit Jaya
- Bank Industri
- Bank Jakarta
- Bank Astria Raya
- Bank Guna Internasional
- Bank Dwipa Semesta
- Bank Kosagraha Semesta
- Bank Citrahasta Danamanunggal
- Bank Andromeda
- Bank Mataram Dhanaarta
Penutupan 16 bank yang tidak solvent merupakan bagian dari restrukturisasi sektor keuangan, bahkan dikabarkan tindakan ini merupakan syarat awal dari pinjaman IMF. Pencabutan izin usaha terhadap 16 bank yang semula dimaksudkan untuk penyehatan perbankan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat, ternyata justru berakibat sebaliknya, yang sangat jauh dari perhitungan semula. Masyarakat yang mengetahui bahwa jumlah simpanan yang dibayarkan pada 16 bank yang dilikuidasi hanya sebesar Rp 20 juta, meski jumlah simpanannya diatas angka itu, melakukan penarikan dana tunai secara besar-besaran dan pemindahan dana ke bank-nak yang dianggap lebih sehat. Akibatnya, bank-bank yang dianggap kuat juga ikut terkena dampak krisis kepercayaan tersebut.
Pembentukan BPPN
BPPN dientuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.
Agar dapat melakukan misinya, BPPN dibekali seperangkat kewenangan yang tertuang dalam Keppres No. 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai landasan hukum operasional. Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Perbankan, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN (PP 17/1999) yang secara lebih rinci mengatur landasan hukum operasional BPPN. Berbagai kewenangan BPPN yang telah ditetapkan dalam UU Perbankan dijabarkan agar diapat dioperasionalkan secara jelas, baik menyangkut persyaratan maupun tatacaranya.
Dalam upaya penyelesaian BLBI, pemerintah melakukan terobosan, melalui tiga skema, yaitu:
- Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), yang diberlakukan bagi pemegang saham (PS) Bank yang menyerahkan aset dan nilainya mencukupi untuk melunasi kewajibannya.
- Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA) bagi PS Bank yang menyerahkan aset namun nilainya kurang dari nilai kewajibannya
- PS Bank yang sama sekali tidak dapat menyerahkan aset, diminta menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU).
Ada lima pemegang/pemilik saham bank yang mengikuti dan memenuhi skema MSAA ini. Penyerahan asset mereka dihitung jumlah dan nilainya oleh konsultan keuangan dan hukum lokal dan internasional yang ditunjuk pemerintah. Mereka adalah Sjamsul Nursalim (pemilik BDNI), Soedono Salim (BCA), Ibrahim Risjad (RSI), M Hasan (BUN), Sudwikatmono (Surya).
Mereka menandatangani MSAA 21 September 1998. Pada 25 Mei 1999 Menteri Keuangan dan Kepala BPPN memberikan kepadanya Surat Pembebasan dan Pelepasan (Release and Discharge). Hal tersebut kemudian dipertegas melalui akta “Letter of Statement” yang dibuat di depan notaris. Isinya, antara lain, menytakan para pemilik bank yang menandatangani MSAA telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran BLBI dan menegaskan pemerintah telah memberikan Release and Discharge.
Dengan surat tersebut pemerintah menjamin dan membebaskan para pemegang saham dari tuntutan hukum apa pun di kemudian hari berkaitan dengan penyelesaian BLBI. Jaminan kepastian hukum atas penyelesaian BLBI ini kemudian dipayungi Undang Undang RI No.25 tahun 2000 (“UU Propenas”), Ketetapan MPR No. X/2001, Ketetapan MPR No.VI/MPR/2002 serta Inpres No.8 Tahun 2002.
Di zaman kepemimpinan Glenn Yusuf, BPPN melengkapi organisasinya dengan divisi Asset Management Credit (AMC) dan Asset Management Investment (AMI). AMC menangani kredit bermasalah dari bank-bank yang ditutup atau diambil pemerintah. Sementara AMI menangani aset bank atau pemilik bank. Nilai seluruh aset yang berada di tangan AMC dan AMI berjumlah Rp. 640 triliun.
Selain mereka yang menandatangani MSAA, ada empat pemilik bank, yaitu Kaharudin Ongko, Samadikun Hartono, Usman Admadjaja, dan Hokiarto, menyepakati Master Refinancing and Notes Issues Agreement (MRA). Total nilai aset sembilan konglomerat yang diserahkan ke BPPN berjumlah Rp. 111,643 triliun.
Bersamaan dengan kesepakatan itu, BPPN bersama pemilik bank membentuk perusahaan induk untuk mengelola aset, misalnya saja PT. Holdiko Perkasa untuk aset Soedono Salim atau PT. Tunas Sepadan Investama bagi Sjamsul Nursalim.
Selain MSAA dan MRA, BPPN juga menawarkan skema Akta Pengakuan Utang (APU) bagi para pengusaha. Seharusnya seluruh aset sudah berada di tangan BPPN bisa dijual. Kenyataannya, hal itu tak terjadi karena berbagai sebab. Ada yang karena dokumen tidak lengkap, saham pemilik sudah diserahkan kepada kreditur lain, atau perbedaan valuasi atas aset yang diserahkan ke BPPN.
BPPN melaksanakan kebijakan baru dalam upaya percepatan serta optimalisasi tingkat pengembalian meliputi bidang: penyelesaian Asset Transfer Kit (ATK), Restrukturisasi Utang, dan Penjualan Hak Tagih. Cara yang ditempuh adalah menjual langsung dan tender.
Dalam rangka penyelesaian BLBI yang dikucurkan, Pemerintah menghimbau para pemegang saham pengendali bank untuk menyelesaikan kewajiban bank dengan janji tidak akan mengambil tindakan hukum apapun terhadap bank, pemegang saham pengendali, dan para pengurus bank terhadap pelanggaran peraturan bank (bilamana ada).
Khusus mengenai pemilik BDNI Sjamsul Nursalim, meskipun berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan peraturan perbankan yang berlaku waktu itu pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian bank, yang bersangkutan secara kooperatif dan itikad baik bersedia ikut membayar kewajiban BDNI. Sjamsul Nursalim dan Pemerintah kemudian mencapai kesepakatan bahwa jumlah kewajiban BDNI yang harus ditanggung adalah sebesar Rp28,4 Trilyun, yang akan diselesaikan dengan pembayaran setara tunai sejumlah Rp 1 T dan penyerahan aset berupa saham-saham perusahaan senilai Rp 27,4 T. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (Perjanjian PKPS) dalam bentuk Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) yang ditandatangani pada tanggal 21 September 1998.
Dalam menentukan kewajiban yang akan dibebankan kepada Sjamsul Nursalim, terlebih dahulu dilakukan penghitungan kewajiban dan aset BDNI. Selisihnya kemudian ditetapkan menjadi kewajiban Sjamsul Nursalim. Adapun asumsi yang digunakan dalam menghitung aset bank adalah bahwa ekonomi dalam keadaan normal (normalized economic condition), yang artinya kredit-kredit yang menjadi aset bank tidak dalam kondisi terdampak krisis ekonomi saat itu. Demikian pula penilaian aset-aset perusahaan yang akan diserahkan menggunakan asumsi normalized economic condition, bukan berdasarkan nilai market pada kondisi krisis ekonomi saat itu.
Setelah Sjamsul Nursalim memenuhi kewajibannya berdasarkan MSAA, pada tanggal 25 Mei 1999, Pemerintah menerbitkan 2 surat Release and Discharge (R&D) yang menyatakannya telah memenuhi kewajiban berdasarkan MSAA. Karenanya, ia dibebaskan dari kewajiban pembayaran BLBI lebih lanjut. Pemerintah juga berjanji tidak akan melakukan tindakan hukum apapun terhadap BDNI, Sjamsul Nursalim dan pengurus bank. R&D tersebut dikuatkan dengan akta otentik berupa Akta Letter of Statement No. 48 tertanggal 25 Mei 1999 yang dibuat dihadapan notaris dimana Pemerintah menyatakan pemenuhan MSAA oleh SN dan diberikannya R&D kepada SN.
Setelah terjadi penggantian pemerintahan dari Presiden BJ Habibie ke Abdurrahman Wachid, kebijakan penyelesaian berdasarkan MSAA dengan pola asset settlement dipermasalahkan. Ada keinginan untuk mengubahnya menjadi pola cash settlement. Pemerintahan baru juga mengabaikan kebijakan sebelumnya dalam menetapkan asumsi normalized economic condition dalam menilai aset yang telah diserahkan. Muncullah klaim dari BPPN pada bulan November 1999 bahwa Sjamsul Nursalim melakukan misrepresentasi mengenai hutang petambak kepada BDNI. Hal ini telah dibantah oleh Sjamsul Nursalim. Selain itu, berdasarkan perjanjian MSAA, Sjamsul Nursalim tidak dianggap berhutang kepada BPPN atas klaim dari BPPN sebelum klaim tersebut dibuktikan terlebih dahulu dan diputuskan oleh pengadilan perdata.
Akibat inkonsistensi kebijakan penyelesaian BLBI yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, kemudian diterbitkanlah UU Propenas (UU No. 25/2000) agar diberikan kepastian hukum bagi pihak yang telah menyelesaikan kewajibannya. Selanjutnya Tap MPR No. X tahun 2001 memerintahkan kepada Presiden agar konsisten melaksanakan MSAA. Upaya mengubah MSAA kemudian dihentikan. Presiden Megawati kemudian menerbitkan Inpres No. 8/2002 yang pada intinya memerintahkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang saham yang sudah dengan kooperatif menyelesaikan kewajiban mereka.
Pemberian SKL
Dalam rangka melaksanakan UU Propenas, TAP MPR dan Inpres, BPPN di bawah kepemimpinan Sjafruddin Arsyad Temenggung mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada tanggal 26 April 2004. Salah satu pertimbangan BPPN dalam memberikan SKL adalah adanya Laporan Audit Investigatif BPK tahun 2002 yang menyatakan MSAA telah dipenuhi (closing) pada tanggal 25 Mei 1999. SKL diberikan kepada lima pemilik bank yang menandatangani MSAA, yaitu Soedono Salim, Sudwikatmono, Mohamad Hasan, Sjamsul Nursalim dan Ibrahim Risjad.
BPPN menerbitkan SKL setelah melalui serangkaian pembahasan resmi dalam Rapat Kabinet dan disetujui oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Dalam rapat KKSK tanggal 13 Februari 2004, yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/Ketua KKSK Dorodjatun Kuntjoro-jakti, disetujui penerbitan SKL tersebut. Sebelumnya, telah diadakan Rapat Kabinet pada 11 Februari 2004 yang dihadiri oleh Dorodjatun, Menteri Keuangan Boediono, Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi, Menteri Perdagangan Rini Soewandi, dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie.
Setelah lima tahun bertugas menyehatkan perbankan nasional, BPPN kemudian dibubarkan. Dalam perjalanannya, BPPN telah berganti pucuk pimpinan sebanyak tujuh kali. Masing-masing adalah Bambang Subianto, Iwan Prawiranata, Glenn M.S. Yusuf, Cacuk Sudarijanto, Edwin Gerungan, dan I Putu Gde Ary Suta. Terakhir adalah Syafruddin A. Temenggung.
BPPN berhasil menyetor dana ke kas negara sebesar Rp 163 triliun. Nilai aset yang dikuasai BPPN pada awal berdirinya lima tahun silam sekitar Rp 650 triliun. Mengenai tingkat pengembalian aset, menurut perhitungan BPPN, mencapai 28 persen lebih.